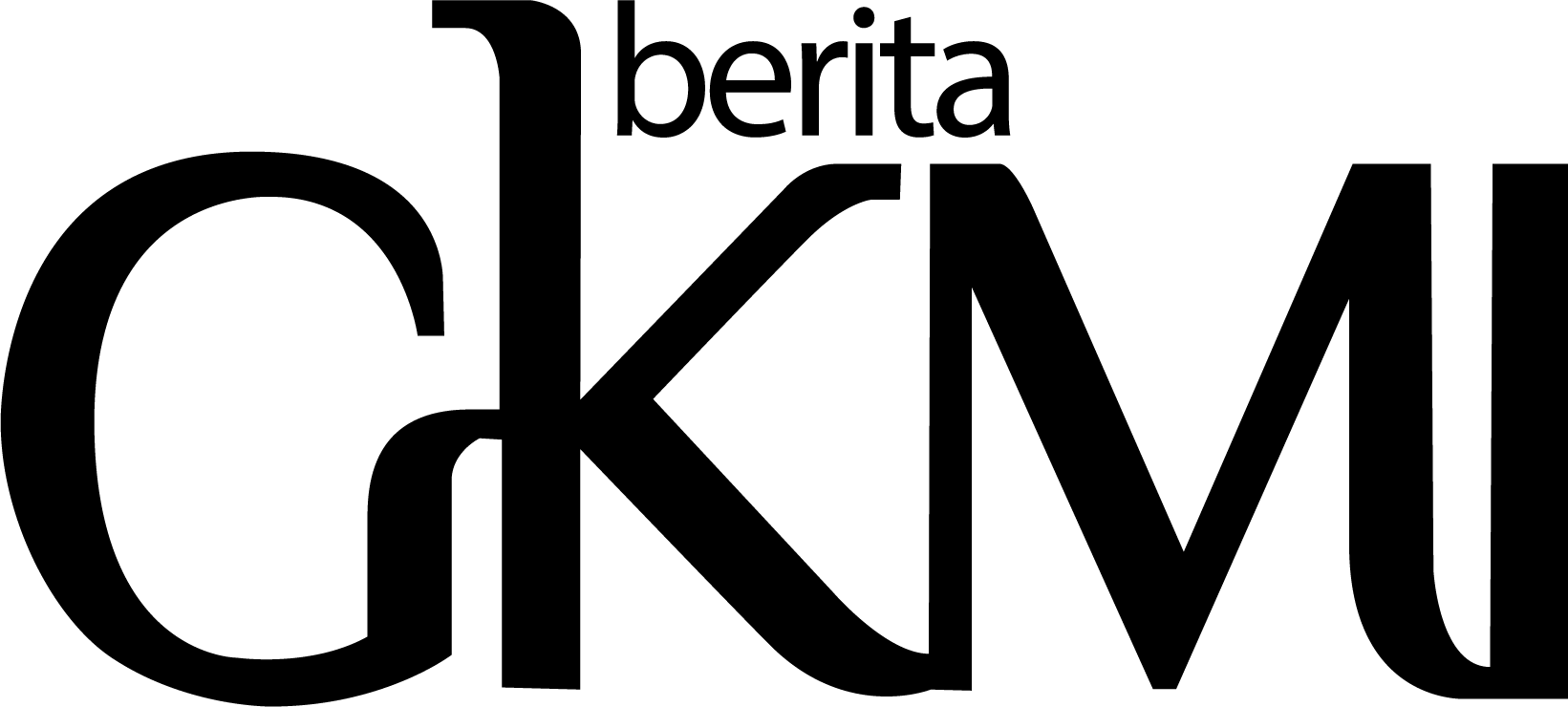Kekayaan, Kekuasaan dan Suara Hati
Date Published

Kekayaan (wealth) adalah kelimpahan kepemilikan atas sumber daya dan/atau materi. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain. Tidak ada yang salah dengan kekayaan, pun demikian dengan kekuasaan. Kekayaan dan kekuasaan adalah anugerah Tuhan bagi manusia. Tuhan mengizinkan manusia menjadi kaya dan berkuasa. Beberapa tokoh Alkitab adalah orang kaya, bahkan Salomo adalah orang terkaya di dunia pada zamannya (1 Raja-raja 10: 23).
Tetapi aneh bahwa Alkitab memperingatkan manusia supaya tidak mengejar kekayaan dan kekuasaan (1 Timotius 6: 9). Saya mengutip perkataan David W. Boshart, Ph.D, Presiden Anabaptist Mennonite Biblical Seminary (AMBS) yang disampaikan dalam kuliah umum di Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), yaitu istilah “ateisme fungsional”. Ateisme fungsional menurut Boshart secara sederhana dipahami sebagai kemandirian diri manusia, dalam pengertian bahwa segala persoalan yang terjadi di dunia ini dapat diselesaikan sendiri oleh manusia, tanpa membutuhkan pertolongan Tuhan.

Sumber: lightofchristjourney.com
Dengan cara demikian, manusia berdiri sendiri secara total (otonomi total) dalam menghadapi segala problematika yang terjadi di dunia ini, salah satunya dengan uang yang dimilikinya. Dengan uang orang dapat melakukan dan membeli apa saja, termasuk kekuasaan. Dengan kekuasaan orang dapat melakukan apa saja, termasuk menumpuk uang (kekayaan). Apalagi dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, manusia semakin percaya kepada dirinya sendiri sebagai problem solver.
Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan kekayaan dan kekuasaan. Tuhan tidak membenci orang kaya dan para penguasa. Yang salah adalah ketika orang melabuhkan hatinya pada kekayaan dan kekuasaan, dan menjadikan mereka sebagai ilah. Masalah muncul ketika kekayaan dan kekuasaan menjadi tambatan hati. Kita tahu perkataan nabi Yeremia bahwa hati itu licik melebihi segala sesuatu (Yeremia 17: 9).
Dalam kapasitas sebagai orang benar yang masih berdosa, hati bisa saja berbelok, atau dibelokkan menjadi gembala dalam bertindak.
Oleh karena itu kita harus bijaksana untuk tidak harus selalu percaya kepada suara hati, karena hati manusia tidak pernah dirancang Tuhan untuk diikuti, walaupun Tuhan dapat menggunakan suara hati untuk menyatakan tuntunan-Nya. Namun, Tuhan tidak pernah mencipta hati untuk menggantikan-Nya, apalagi diikuti. Justru hati yang harus tunduk dan mengikuti apa kata Tuhan. Hati harus diarahkan kepada Tuhan dan supaya percaya kepada Tuhan, sehingga dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendak-Nya.

Sumber: seminary.grace.edu
Gembala kita bukan hati, melainkan Yesus Kristus. Ia tidak berkata, “Jangan gelisah hatimu, percaya saja apa yang dikatakan hatimu”. Namun Ia berkata, “Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Ku” (Yohahes 14: 1).
Tidak selalu percaya kepada suara hati menghindarkan kita dari sikap dan tindakan yang bersandarkan kepada pengertian sendiri. Dengan kata lain, kita tidak harus bersandar kepada kesimpulan yang diambil dari persepsi kita sendiri. Kesimpulan dari persepsi kita tidak akan mampu menanggung semua beban pergumulan realitas yang kita hadapi.
Apa yang dilakukan nenek moyang kita di Taman Eden seharusnya menempelak kita untuk tidak bersandar kepada pengertian, kesimpulan, dan persepsi diri sendiri. Tuhan ingin kita sebagai keturunannya tidak mewarisi sikapnya yang sembrono itu. Oleh karena Tuhan memerintahkan kita untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan, supaya dari sana terpancar kehidupan (Amsal 4: 23). Hati yang hidup dan menyala adalah hati yang bersandar pada Tuhan dan dipersembahkan kepada Tuhan, bukan pada kekayaan dan kekuasaan. (MR)
Salam perdamaian,
hehi